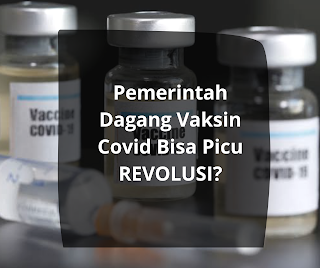Kedaulatan di Hulu Migas
Kamis (12/6/2014) lalu saya terlibat dalam focus group discussion bertema Politik Migas Menuju Kedaulatan Energi dan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini digelar Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang atas gagasan ketua jurusan, Rudi Rohi, satu dari sedikit akademisi muda progresif di NTT.
Dua puluhan peserta hadir dari beragam latar belakang. Ada politisi kawakan, aktivis muda, redaktur surat kabar lokal dan wartawan senior koran nasional, pimpinan organisasi pergerakan mahasiswa, pekerja LSM, dosen sejumlah perguruan tinggi di Kupang, dan pejabat pemprov NTT.
Sebelumnya ada kecemasan diskusi akan berlansung kering dan karena itu lekas bubar. Hal ini didasari prasangka bahwa persoalan migas minim-perhatian khalayak NTT. Apalagi temanya kedaulatan energi yang sepintas tampak jauh dari keseharian masyarakat NTT. Itu sebabnya, begitu diskusi dimulai, wartawan senior Kompas Frans Sarong menyampaikan tema diskusi ini lebih tepat dibicarakan di Jakarta.
Tetapi beberapa menit setelah FGD berlangsung kecemasan itu beranjak pudar. Nyatanya percakapan antusias berlangsung selama 7 jam tanpa banyak peserta meninggalkan ruangan. Menarik, meski hanya beberapa orang yang memasok data dan informasi terkini tentang problem hulu dan hilir migas, gairah berdiskusi tetap memenuhi seisi ruangan. Tampaknya ada rindu menggebu pada kedaulatan negara dalam urusan energi. Peserta menyadari pentingnya kedaulatan dalam industri migas sebagai landasan kemandirian bangsa dalam menjamin ketahanan energi, yang selanjutnya berdampak pada kuatnya industri nasional.
Maka tidak heran jika akhirnya FGD menghasilkan keseragaman pandangan peserta tentang sejumlah hal, seperti pentingnya penguasaan nasional atas industri migas melalui peningkatan peran Pertamina; perlunya perubahan paradigma dari energi to devisa menjadi energi to energi; keadilan kemanfaatan energi antar wilayah, sektor, dan generasi; penguatan partisipasi rakyat dalam mendukung partisipasi BUMD dalam memanfaatkan 10 persen participating interest dalam PSC migas; hingga pencabutan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas yang berkarakter neoliberal.
Mengingat keterbatasan ruang, artikel ini fokus pada aspek penguasaan negara di sektor hulu migas.
Sudah jamak diketahui, mayoritas penguasaan upstream migas tanah air berada di tangan pemodal asing, baik swasta pun milik negara asing. Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina hanya menguasai 17 persen blok migas, itupun kebanyakan sumur tua yang diwariskan perusahaan asing setelah kontrak berakhir. Sementara pada blok migas strategis (cadangan besar), penguasaan pertamina tidak lebih dari 5 persen.
Dominasi asing, ditambah lambatnya penemuan cadangan migas baru dan tingginya konsumsi BBM domestik menjadi mantra resource curse bagi bangsa ini. Karena itu selain upaya-upaya penghematan konsumsi energi final; konversi BBM ke BBG, panas bumi, tenaga matahari, dan bioenergi; dan perbaikan fiscal policy untuk mendorong eksplorasi cadangan migas baru; juga mutlak diperlukan strategi untuk meningkatan porsi penguasaan nasional pada lini upstream migas.
Persoalannya, bagaimana strategi yang tepat? Dalam FGD, Ketua PRD NTT Yosep Asafa menjelaskan berbagai usulan strategi yang telah lama diteriakkan kelompoknya. Mulai dari aneka varian nasionalisasi yang mencontoh pengalaman negara lain, hingga yang paling lunak adalah renegosiasi kontrak agar lebih menguntungkan negara.
Beragam alternatif langkah penguatan peran negara yang diangkat itu penting. Tetapi saya perlu menyarankan sikap hati-hati, tidak menyamakan industri hulu migas dengan industri strategis lain. Ada kekhasan dalam industri hulu migas yang membuat strategi nasionalisasinya tidak semudah, misalnya, jika kita menasionalisasi (kembali) pabrik baja Krakatau Steel. Kekhasan itu adalah besarnya biaya eksplorasi di satu sisi dan ketidakpastian kesuksesan eksplorasi di sisi lain.
Beberapa teman yang bekerja di perusahaan hulu migas memberitahu bahwa biaya untuk satu sumur eksplorasi untuk membuktikan hasil studi berkisar 30 juta USD. Karena ratio suksesnya 1 berbanding 10 sumur, maka investor perlu menyiapkan dana 300 juta USD atau setara 3 triliun IRD (anggaplah 1 USD setara 10ribu IRD).[1] Ini belum termasuk biaya studi dan pemeliharaan fasilitas selama masa eksplorasi yang besarnya juga bukan main. Jika memang kandungan migas terbukti (P1, proven) dan bisa lanjut ke tahap produksi, biaya eksplorasi akan diganti dari lifting minyak nanti (skenario recovery of operating costs, populer sebagai cost recovery dalam production sharing contract, PSC). Persoalannya jika kadungan migas tak terbukti atau tidak cukup ekonomis, perusahaan kehilangan triliunan rupiah.[2] Kondisi ini secara alamiah menyebabkan industri hulu migas berstruktur oligopoli dengan penanda khasnya high barrier to entry.
Barrier berupa high cost investment itu juga menghadang Pertamina. Pertamina kesulitan mendapat kredit perbankan untuk aktivitas eksplorasi. Selain karena berisiko tinggi, penguasaan asing di dalam perbankan nasional menjauhkan mereka dari kepedulian pada kepentingan nasional.[3] Yang lebih gawat, Indonesia tidak memiliki model reinvestasi penghasilan migas melalui petroleum fund. Padahal inilah mekanisme yang memungkinkan ketersediaan dana bagi aktivitas eksplorasi oleh Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Problem ini adalah warisan masa lampau yang tanpa pikir panjang diteruskan pemerintahan demi pemerintahan. Pemerintah kita lebih suka melanjutkan pola lama, PSC. Padahal pola ini digagas 50an tahun lampau ketika Indonesia belum lama merdeka sehingga belum memiliki cukup anggaran untuk melakukan eksplorasi mandiri. PSC mengadopsi model paron, bagi hasil dalam mode produksi pertanian pangan a la feodal. Dengan pola ini, modal asing mengerjakan lahan migas kita, dan sebagai tuan tanah, pemerintah menerima bagi hasil.
Ketiadaan petroleum fund menyandera kita untuk tetap butuh keterlibatan modal asing, terutama pada fase eksplorasi, yang–sayangnya--tidak terelakan berarti kelanjutan peran mereka di tahap eksploitasi. Nasionalisasi yang “kasar,” misalnya secara sepihak memutuskan kontrak yang sedang berjalan dan memindahkan penguasaan ke tangan Pertamina, meski dengan ganti rugi fair atas nilai aset akan berbuntut keengganan masuknya investor baru dan karena itu menghambat upaya penemuan cadangan migas baru. Padahal, rendahnya replacement reserve ratio merupakan salah satu sebab terus turunnya angka lifting minyak nasional.
Lantas bagaimana?
Di sini kita perlu bersikap “tricky,” meningkatkan porsi penguasaan Pertamina pada blok migas di tahap eksploitasi, sementara eksplorasinya–selama belum ada petroleum fund—masih mengandalkan modal asing. Kesannya modal asing kita "kadali". Tak mengapa karena sebagaimana kata Jokowi (debat capres putaran kedua) proteksi bagi industri domestik sering berlaku dengan cara ini.
Model ini memadukan konsep PSC dengan konsep konsesi a la negara-negara penghasil migas di Timur Tengah. Arab Saudi misalnya menambahkan hak partisipasi progresif pemerintah melalui perusahaan negara pada saham kontraktor kerja sama. Dengan hak ini, Arab Saudi kini menguasai 100 persen saham Aramco dan mengubah perusahaan yang semula milik Standar Oil asal AS itu sebagai national oil company (NOC). Dengan pemaduan ini, dalam kontrak kerja sama dimasukkan klausul penguasaan progresif Pertamina pada saham kontraktor di tahap eksploitasi.
Selain memperbesar porsi negara (inkind migas, pun devisa), cara ini bisa menyelesaikan persoalan ketidakpastian data produksi migas dan penyimpangan cost recovery. Menjadi bagian dalam perusahaan selalu lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian dibanding bertindak sebagai pihak eksternal.
Agar investor tetap tertarik melakukan eksplorasi, Sebagai gantinya bisa diberikan insentif fiskal khusus. Misalnya berupa pemotongan PPN bagi peralatan impor dalam kegiatan eksplorasi, atau juga sistem fiskal yang fleksibel terhadap tingkat kesulitan wilayah eksplorasi. Kebijakan yang terakhir ini mendapat penekanan khusus dalam dokumen visi-misi-program capres Jokowi-JK.
Dalam putaran kedua debat capres beberapa waktu lalu, Prabowo tepat dengan menyatakan pentingnya renegosiasi kontrak investasi asing yang merugikan negara. Demikian pula Jokowi benar dengan menekankan perlunya kecermatan kalkulasi untung-rugi antara peran asing, swasta nasional, dan BUMN dalam kontrak pengelolaan SDA. Dalam konteks migas, kedaulatan dalam industri hulu migas merupakan syarat bagi kemandirian bangsa dalam menjamin ketahanan energi. Tetapi jalan menuju penegakkan kedaulatan itu perlu kalkulasi matang agar tidak kontraproduktif.
Yang terpenting agar kedaulatan itu sungguh terwujud, pemerintah mendatang perlu mengubah paradigma, dari “migas untuk devisa” menjadi “migas untuk energi,” untuk industrialisasi nasional. Dengan berparadigma migas untuk energi bagi industrialisasi nasional, pemerintah tidak perlu lagi risau jika harga minyak di dalam negeri, terutama crude oil bagi kilang domestik dijual lebih murah dibanding harga internasional. Karena dengan paradigma ini, minyak mentah bukan lagi sumber devisa dan penggelembung pundi-pundi penerimaan negara. Sandaran devisa pindah ke ekspor produk pabrik-pabrik di dalam negeri yang meningkat daya saingnya karena pasokan energi murah-memadai. Sumber utama penenerimaan negara dari dalam negeri bergeser ke peningkatan penerimaan pajak dari menjamurnya badan usaha. Dengan paradigma baru ini, perhatian utama pemerintah tidak sempit pada government take tetapi lebih luas pada tersedianya lapangan kerja dan kemandirian bangsa.***
____
[1] Menteri ESDM Jero Wacik bahkan mengatakan biaya 1 sumur bor onshore 60 juta USD dan offshore mencapai 100 juta USD (“Eksplorasi Migas Perusahaan Dalam Negeri Diprioritaskan.” Suara Merdeka.com, May 27, 2014. )
[2] Sepanjang 2009-2013, 12 KKKS migas asing merugi Rp 19 triliun gagal menemukan migas di 16 blok eksplorasi laut dalam di Indonesia. (“12 KKKS Asing Rugi Rp19 Triliun Cari Cadangan Migas Di Laut Dalam Indonesia.” Kementerian ESDM. Accessed June 19, 2014. http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6319-12-kkks-asing-rugi-rp19-triliun-cari-cadangan-migas-di-laut-dalam-indonesia.html.)
[3] Dua tahun lalu, 6 dari 10 bank dengan asset terbesar yang menguasai 62,87 persen industri perbankan nasional berada di bawah kendali modal asing (“Kekuatan Modal Asing Di Bank Dikhawatirkan.” JPNN.com, May 28, 2012.) Peningkatan dominasi asing tidak lepas dari liberalisasi keuangan yang dilegitimasi UU 29 Tahun 1999 yang memperbolehkan pihak asing menguasai 99% saham di perbankan nasional. Baru pada pembahasan RUU perbankan yang baru, yang hingga pertengahan Juni ini belum rampung, DPR membatasi kepemilikan modal asing maksimum 40%, lebih rendah dari janji pemerintahan SBY kepada negara anggota WTO yang sebesar 49% (“DPR Setuju Saham Asing di Bank Nasional Maksimal 40%.”Bisnis.com, June 17, 2014.)
____
Published on Berdikari Online, 19/06/2014
Oleh George Hormat Kulas
Ketua Sanggar Ekonomi Gotong Royong | Segoro NTT
Untuk kepentingan pengutipan, sila gunakan format bibliography Chicago Manual of Style 16th edition berikut
Kulas, George Hormat. “Kedaulatan Di Hulu Migas.” Berdikari Online, June 19, 2014. http://www.berdikarionline.com/opini/20140619/kedaulatan-di-hulu-migas.html.