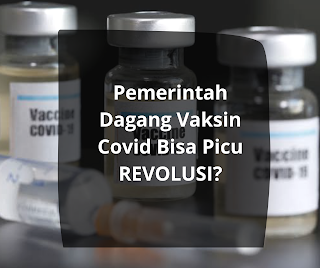Jenderal Moeldoko dan Krisis Hegemoni Rejim Pencitraan
Ketika mendapat tautan berita "Moeldoko: Investasi Terancam, TNI Turun Tangan" (Kompas.com, 4/9/2013), saya sedang membaca opini William I. Robinson, "Crisis of Humanity: Global Capitalism Breeds 21st Century Fascism" (truth.com, 26/8/2013). Tepat seminggu kemudian, ratusan aparat kepolisian, TNI, preman, dan pegawai Perhutani mengepung sekretariat Serikat Tani Indramayu (STI) di Bojong Raong, Indramayu, Jawa Barat.
Pernyataan Moeldoko menuntut kita waspada akan kembalinya militerisme. Bagi saya, segala bentuk campur tangan militer dalam domain sipil adalah militerisme. Urusan investasi dan perselisihan terkait itu adalah ranah sipil. Pendekatan TNI bersifat koersif, anti-demokrasi.
Robinson, professor sosiologi University of California menulis tentang fitur fasisme abad 21 sebagai modalitas kontrol sosial dari negara yang mengabdi kepada kepentingan kapitalisme global untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Termasuk di dalam Fasisme abad 21 ini adalah militerisme, maskulinisasi ekstrim, homofobia, rasisme, dan mobilisasi rasisme melawan kelompok-kelompok yang dijadikan kambing hitam atas krisis ekonomi. Topik serupa ia tulis dalam “Global Capitalism and 21st Century Fascism” dan “Global Rebellion: The Coming Chaos?“ (Aljazeera.com, 8/5 dan 4/12/2011). Pandangan ini dilandaskan pada studi Stuart Hall, dkk (Policing the Crisis, 1979) terhadap restrukturisasi kapitalisme dalam merespon krisis 1970an. Dengan istilah lebih halus “kebangkitan neokonservatisme,” David Harvey berkesimpulan serupa (Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis, 2009).
Ringkasnya, krisis kapitalisme yang berdampak PHK, kenaikan biaya hidup, dan pemotongan jaminan sosial meningkatkan perlawanan kelas pekerja terhadap kapitalisme dan representasi politiknya. Terjadi krisis hegemoni. Mekanisme konsesus kontrol sosial tidak lagi efektif sehingga pendekatan dominasi melalui instrumen koersif menguat.
Kecocokan pernyataan Moeldoko dengan peringatan Robinson perlu dikonfirmasi pada kondisi dan arah krisis ekonomi; masifnya perlawanan rakyat; dan krisis hegemoni rejim yang berkuasa. Tiga hal ini adalah basis objektif bagi posisi subjektif TNI yang disampaikan Moeldoko.
Krisis neoliberalisme sejak 2008 belum sungguh usai. The Economist (7/9/2013) “Where’s the next Lehman?” menyatakan, meski ekonomi dunia relatif lebih aman, terdapat peluang besar terjadinya krisis berikut. “Today’s danger zones are elsewhere. ... they could produce enough turmoil to hit growth hard.” Jumat (6/8) Depnaker Amerika Serikat melaporkan tingkat partisipiasi angkatan kerja di bulan Agustus turun menjadi 63,2 persen, angka terendah sejak 1978. Sejak awal 2010, tingkat partisipasi angkatan kerja di AS telah turun 1,6 poin (ABCNews.com, 6/9.2013).
Indonesia tampaknya termasuk danger zones. Keterpurukan nilai tukar rupiah menunjukkan rapuhnya ekonomi negeri ini karena bersandar pada tingginya impor, aliran hot money, dan utang luar negeri. Bahkan ketika angka-angka makroekonomi cukup baik, pertumbuhan ekonomi kita belum memuaskan dalam menyerap angkatan kerja, menyediakan kebutuhan pokok murah, dan mempersempit kesenjangan minoritas kaya dan mayoritas miskin.
Krisis kapitalisme meningkatkan perlawanan masyarakat yang dirugikan, melibatkan strata sosial-ekonomi dan teritori yang sebelumnya adem ayem. Gerakan Occupy Wall Street yang berpusat di jantung neoliberalisme, AS dua tahun lalu adalah salah satu petunjuk penting.
Di Indonesia, aksi protes rakyat selain kian sering, kian banyak peserta, kian luas sebaran sektor dan teritori; juga kian berani metodenya, berupa pendudukan fasilitas umum hingga pembakaran simbol kekuasaan. Ini menunjukkan krisis hegemoni pemerintahan SBY. Politik pencitraan dan aksi Humas tidak lagi efektif menenangkan rakyat yang resah dan marah oleh kebijakan ekonomi neoliberalnya.
Hantaman keras bagi hegemoni pemerintahan SBY juga menerpa langsung pilar pencitraannya: anti-korupsi. Sejumlah skandal korupsi raksasa yang paling menyita perhatian publik jutru melibatkan lingkaran-dalam kekuasaan.
Kemunculan bintang baru, Jokowi yang mewakili citra bertolak-belakang dengan SBY juga berkontribusi pada krisis hegemoni ini. Dikatakan Mulyana W. Kusumah, Jokowi membuat rakyat “...tidak lagi mendasarkan pilihan pada tokoh yang mengedepankan bentuk pencitraan palsu, yaitu memadukan penampilan pribadi yang direkayasa atau dengan gagasan pernyataan publik yang terkesan santun bergaya akademik” (Berdikarionline.com, 26/8/2013).
Mendekati Pemilu, saling kritik dan bongkar bobrok antar elit meningkat, menyebabkan popularitas SBY dan lingkarannya sebagai sasaran tembak utama kian terperosok. Selain itu, fokus kebijakan pada pembangunan infrastruktur berpotensi menuai banyak perlawanan karena watak kejar setoran birokrat yang takut repot melibatkan rakyat dalam merencanakan pembangunan. Nyaris setiap hari ada berita perlawanan rakyat yang menolak lahannya diambilalih untuk proyek infrastruktur.
Pemulihan kapitalisme dari krisis butuh agen politik yang efektif. Maka pernyataan Moeldoko adalah alaram pergeseran karakter ideologis negara dalam meraih kepatuhan publik, dari negara demokrasi prosedural menjadi negara polisionil; dari hegemoni berbasis pencitraan menuju dominasi militeristik.
Kaum pro-demokrasi perlu segera menggagas langkah bersama demi warisan reformasi 1998, demokrasi dan demiliterisasi domain sipil. ***
____________________
Published on Berdikarionline.com, 15/9/2013
Oleh George Hormat Kulas
Ketua Sanggar Ekonomi Gotong Royong | Segoro NTT
Pernyataan Moeldoko menuntut kita waspada akan kembalinya militerisme. Bagi saya, segala bentuk campur tangan militer dalam domain sipil adalah militerisme. Urusan investasi dan perselisihan terkait itu adalah ranah sipil. Pendekatan TNI bersifat koersif, anti-demokrasi.
Robinson, professor sosiologi University of California menulis tentang fitur fasisme abad 21 sebagai modalitas kontrol sosial dari negara yang mengabdi kepada kepentingan kapitalisme global untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Termasuk di dalam Fasisme abad 21 ini adalah militerisme, maskulinisasi ekstrim, homofobia, rasisme, dan mobilisasi rasisme melawan kelompok-kelompok yang dijadikan kambing hitam atas krisis ekonomi. Topik serupa ia tulis dalam “Global Capitalism and 21st Century Fascism” dan “Global Rebellion: The Coming Chaos?“ (Aljazeera.com, 8/5 dan 4/12/2011). Pandangan ini dilandaskan pada studi Stuart Hall, dkk (Policing the Crisis, 1979) terhadap restrukturisasi kapitalisme dalam merespon krisis 1970an. Dengan istilah lebih halus “kebangkitan neokonservatisme,” David Harvey berkesimpulan serupa (Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis, 2009).
Ringkasnya, krisis kapitalisme yang berdampak PHK, kenaikan biaya hidup, dan pemotongan jaminan sosial meningkatkan perlawanan kelas pekerja terhadap kapitalisme dan representasi politiknya. Terjadi krisis hegemoni. Mekanisme konsesus kontrol sosial tidak lagi efektif sehingga pendekatan dominasi melalui instrumen koersif menguat.
Kecocokan pernyataan Moeldoko dengan peringatan Robinson perlu dikonfirmasi pada kondisi dan arah krisis ekonomi; masifnya perlawanan rakyat; dan krisis hegemoni rejim yang berkuasa. Tiga hal ini adalah basis objektif bagi posisi subjektif TNI yang disampaikan Moeldoko.
Krisis neoliberalisme sejak 2008 belum sungguh usai. The Economist (7/9/2013) “Where’s the next Lehman?” menyatakan, meski ekonomi dunia relatif lebih aman, terdapat peluang besar terjadinya krisis berikut. “Today’s danger zones are elsewhere. ... they could produce enough turmoil to hit growth hard.” Jumat (6/8) Depnaker Amerika Serikat melaporkan tingkat partisipiasi angkatan kerja di bulan Agustus turun menjadi 63,2 persen, angka terendah sejak 1978. Sejak awal 2010, tingkat partisipasi angkatan kerja di AS telah turun 1,6 poin (ABCNews.com, 6/9.2013).
Indonesia tampaknya termasuk danger zones. Keterpurukan nilai tukar rupiah menunjukkan rapuhnya ekonomi negeri ini karena bersandar pada tingginya impor, aliran hot money, dan utang luar negeri. Bahkan ketika angka-angka makroekonomi cukup baik, pertumbuhan ekonomi kita belum memuaskan dalam menyerap angkatan kerja, menyediakan kebutuhan pokok murah, dan mempersempit kesenjangan minoritas kaya dan mayoritas miskin.
Krisis kapitalisme meningkatkan perlawanan masyarakat yang dirugikan, melibatkan strata sosial-ekonomi dan teritori yang sebelumnya adem ayem. Gerakan Occupy Wall Street yang berpusat di jantung neoliberalisme, AS dua tahun lalu adalah salah satu petunjuk penting.
Di Indonesia, aksi protes rakyat selain kian sering, kian banyak peserta, kian luas sebaran sektor dan teritori; juga kian berani metodenya, berupa pendudukan fasilitas umum hingga pembakaran simbol kekuasaan. Ini menunjukkan krisis hegemoni pemerintahan SBY. Politik pencitraan dan aksi Humas tidak lagi efektif menenangkan rakyat yang resah dan marah oleh kebijakan ekonomi neoliberalnya.
Hantaman keras bagi hegemoni pemerintahan SBY juga menerpa langsung pilar pencitraannya: anti-korupsi. Sejumlah skandal korupsi raksasa yang paling menyita perhatian publik jutru melibatkan lingkaran-dalam kekuasaan.
Kemunculan bintang baru, Jokowi yang mewakili citra bertolak-belakang dengan SBY juga berkontribusi pada krisis hegemoni ini. Dikatakan Mulyana W. Kusumah, Jokowi membuat rakyat “...tidak lagi mendasarkan pilihan pada tokoh yang mengedepankan bentuk pencitraan palsu, yaitu memadukan penampilan pribadi yang direkayasa atau dengan gagasan pernyataan publik yang terkesan santun bergaya akademik” (Berdikarionline.com, 26/8/2013).
Mendekati Pemilu, saling kritik dan bongkar bobrok antar elit meningkat, menyebabkan popularitas SBY dan lingkarannya sebagai sasaran tembak utama kian terperosok. Selain itu, fokus kebijakan pada pembangunan infrastruktur berpotensi menuai banyak perlawanan karena watak kejar setoran birokrat yang takut repot melibatkan rakyat dalam merencanakan pembangunan. Nyaris setiap hari ada berita perlawanan rakyat yang menolak lahannya diambilalih untuk proyek infrastruktur.
Pemulihan kapitalisme dari krisis butuh agen politik yang efektif. Maka pernyataan Moeldoko adalah alaram pergeseran karakter ideologis negara dalam meraih kepatuhan publik, dari negara demokrasi prosedural menjadi negara polisionil; dari hegemoni berbasis pencitraan menuju dominasi militeristik.
Kaum pro-demokrasi perlu segera menggagas langkah bersama demi warisan reformasi 1998, demokrasi dan demiliterisasi domain sipil. ***
____________________
Published on Berdikarionline.com, 15/9/2013
Oleh George Hormat Kulas
Ketua Sanggar Ekonomi Gotong Royong | Segoro NTT