INI TAHUN NAGA, tetapi yang berjaya kok BELALANG dan ULAT?
Tampaknya belalang jadi newsmaker pada pembukaan tahun Naga di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tidak, dalam bulan ini media massa ramai memberitakan serangan hama belalang dan ulat pada lahan pertanian rakyat di sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur.
Berita di NTTzine.com, misalnya, “Hama Belalang Merusak Pagi Jagung Petani Nangaroro” dan “Hama Belalang dan Ulat Serang Selatan Manggarai." Dampaknya cukup mengkuatirkan, pulahan hingga ratusan hektar lahan padi, jagung, dan kacang-kacangan di desa-desa yang mereka singgahi habis terlalap.
Tentu jalan keluar harus segera ditemukan. Tidak bisa sekedar langkah pemadam kebakaran yang main semprot insektisida. Sebuah pola pertanian yang mengurangi potensi hama harus digalakkan. Tetapi yang bagaimana?
Yucun Lepa, seorang dosen pertanian yang juga ketua DPW PKB NTT, dalam suatu diskusi santai pernah berkata kalau pada prinsipnya alam itu menolak monokultur. Sebuah pertanian monokultur rentan serangan hama. Demikian juga jika keteraturan gulir musim kemarau dan penghujan sedang kacau, sekali gagal tanam, hancur semua sandaran hidup petani.
Saya setuju 100 persen dengan itu. Tetapi penerapannya tidak gampang, bahkan bisa jadi tidak menyelesaikan persoalan. Mengapa?
Mayoritas petani Indoenesia, tak terkecuali Nusa Tenggara Timur adalah petani gurem. Bagi pemilik lahan sempit, adalah lebih menguntungkan menanam satu jenis tanaman di lahannya. Ini adalah hukum ekonomi yang normal: kita harus mencapai jumlah produksi tertentu agar pendapatan melampaui biaya.
Agar lebih jelas, berandai-andai lah kita memiliki satu satuan luas lahan. Ada dua pilihan penggunaan lahan itu. Pertama semuanya digunakan untuk menanam tanaman A, menghasilkan 4 ton per musim panen. Kedua, menanam tiga jenis tanaman (A, B, dan C) dengan musim panen yang berbeda-beda, menghasilkan 1,5 ton A, 2 ton B, dan 0,5 ton C.
Mari kita buat kondisi simulai yang sederhana, dengan mengandaikan:
- Harga per ton A, B, dan C sama
- Satuan berat angkut (untuk dipasarkan) adalah per kelipatan 1 ton.
- Bea angkut per ton adalah Rp X
Maka untuk pilihan pertama, biaya angkut yang kita keluarkan sebesar 4 ton A x Rp X, adalah Rp 4X. Sedangkan untuk pilihan kedua, karena musim panennya berbeda, akan ada tiga kali pengangkutan. Sehingga biaya angkutnya adalah (2 ton A ((pembulatan 1,5 ton)) x Rp X) + (2 ton B x Rp X) + (1 ton C ((pembulatan 0,5 ton)) x Rp X) = Rp 5X.
Lebih untuk pilihan pertama kan?
Ini baru dari satu variable biaya. Belum lagi jika faktor waktu dan kerepotan yang lebih besar jika harus mengurus tiga jenis tanaman dengan kebutuhan treat yang berbeda-beda ikut dipertimbangkan.
Lalu apakah ini kondisi simalakama? Apakah ini trade off yang kejam tanpa win-win solution antara pilihan mengurangi risiko serangan hama atau memperoleh kesejahteraan yang lebih?
Sekitar akhir 1990an hingga awal 2000, Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pernah memperkenalkan “collective farming” dalam program-program tuntutan terkait kesejahteraan petani. Hemat saya, setepat-tepatnya solusi dari kondisi di atas.
Collective farming, sesuai namanya adalah sebuah usaha pertanian bersama. Tetapi tidak sekedar dalam makna kerja gotong-royong sebagaimana lazim dilakukan masyarakat tani. Colletive farming adalah anti-thesis dari coorporate farming atau land-based industry, industri pertanian yang dikuasai perusahaan-perusahaan raksasa.
Jadi bagaimana persisnya sebuah collective farming?
Tunggu artikel seriusnya. Bukan di blog ini, tetapi di nttzine.com. Pantau terus ya.
Salam.
Berita di NTTzine.com, misalnya, “Hama Belalang Merusak Pagi Jagung Petani Nangaroro” dan “Hama Belalang dan Ulat Serang Selatan Manggarai." Dampaknya cukup mengkuatirkan, pulahan hingga ratusan hektar lahan padi, jagung, dan kacang-kacangan di desa-desa yang mereka singgahi habis terlalap.
Tentu jalan keluar harus segera ditemukan. Tidak bisa sekedar langkah pemadam kebakaran yang main semprot insektisida. Sebuah pola pertanian yang mengurangi potensi hama harus digalakkan. Tetapi yang bagaimana?
Yucun Lepa, seorang dosen pertanian yang juga ketua DPW PKB NTT, dalam suatu diskusi santai pernah berkata kalau pada prinsipnya alam itu menolak monokultur. Sebuah pertanian monokultur rentan serangan hama. Demikian juga jika keteraturan gulir musim kemarau dan penghujan sedang kacau, sekali gagal tanam, hancur semua sandaran hidup petani.
Saya setuju 100 persen dengan itu. Tetapi penerapannya tidak gampang, bahkan bisa jadi tidak menyelesaikan persoalan. Mengapa?
Mayoritas petani Indoenesia, tak terkecuali Nusa Tenggara Timur adalah petani gurem. Bagi pemilik lahan sempit, adalah lebih menguntungkan menanam satu jenis tanaman di lahannya. Ini adalah hukum ekonomi yang normal: kita harus mencapai jumlah produksi tertentu agar pendapatan melampaui biaya.
Agar lebih jelas, berandai-andai lah kita memiliki satu satuan luas lahan. Ada dua pilihan penggunaan lahan itu. Pertama semuanya digunakan untuk menanam tanaman A, menghasilkan 4 ton per musim panen. Kedua, menanam tiga jenis tanaman (A, B, dan C) dengan musim panen yang berbeda-beda, menghasilkan 1,5 ton A, 2 ton B, dan 0,5 ton C.
Mari kita buat kondisi simulai yang sederhana, dengan mengandaikan:
- Harga per ton A, B, dan C sama
- Satuan berat angkut (untuk dipasarkan) adalah per kelipatan 1 ton.
- Bea angkut per ton adalah Rp X
Maka untuk pilihan pertama, biaya angkut yang kita keluarkan sebesar 4 ton A x Rp X, adalah Rp 4X. Sedangkan untuk pilihan kedua, karena musim panennya berbeda, akan ada tiga kali pengangkutan. Sehingga biaya angkutnya adalah (2 ton A ((pembulatan 1,5 ton)) x Rp X) + (2 ton B x Rp X) + (1 ton C ((pembulatan 0,5 ton)) x Rp X) = Rp 5X.
Lebih untuk pilihan pertama kan?
Ini baru dari satu variable biaya. Belum lagi jika faktor waktu dan kerepotan yang lebih besar jika harus mengurus tiga jenis tanaman dengan kebutuhan treat yang berbeda-beda ikut dipertimbangkan.
Lalu apakah ini kondisi simalakama? Apakah ini trade off yang kejam tanpa win-win solution antara pilihan mengurangi risiko serangan hama atau memperoleh kesejahteraan yang lebih?
Sekitar akhir 1990an hingga awal 2000, Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pernah memperkenalkan “collective farming” dalam program-program tuntutan terkait kesejahteraan petani. Hemat saya, setepat-tepatnya solusi dari kondisi di atas.
Collective farming, sesuai namanya adalah sebuah usaha pertanian bersama. Tetapi tidak sekedar dalam makna kerja gotong-royong sebagaimana lazim dilakukan masyarakat tani. Colletive farming adalah anti-thesis dari coorporate farming atau land-based industry, industri pertanian yang dikuasai perusahaan-perusahaan raksasa.
Jadi bagaimana persisnya sebuah collective farming?
Tunggu artikel seriusnya. Bukan di blog ini, tetapi di nttzine.com. Pantau terus ya.
Salam.


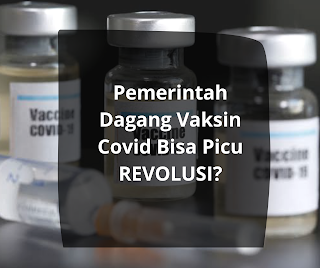
Komentar